Di Balik Luka yang Tak Kasat Mata
Apakah menindas orang lain itu terasa nikmat? Pertanyaan itu sering kali berputar di kepala saya setiap kali melihat berita perundungan berseliweran di media. Entah apa sebabnya, fenomena ini seolah menjadi tren yang tak kunjung usai. Sementara itu, saya di sini hanyalah manusia lemah yang hanya bisa meratapi nasib sebagai salah satu korbannya.
Bagi mereka yang belum pernah merasakannya, mungkin ini terdengar berlebihan. Namun, bagi saya dan banyak korban lainnya, kata yang paling sering terlintas di pikiran hanyalah satu: mati. Pikiran itu datang berulang kali, menghujam, dan seolah menawarkan jalan keluar dari rasa sakit yang tak tertahankan.
Zaman dulu, kesadaran akan kesehatan mental masih menjadi barang mewah yang langka. Orang tua mana yang berpikir untuk membawa anaknya ke psikiater demi menyembuhkan trauma? Boro-boro psikiater, jika seorang anak dimarahi guru di sekolah saja, bukannya mendapat pembelaan atau nasihat lembut, yang ada justru sang anak akan ikut dimarahi di rumah. Kita tumbuh di era di mana "ketangguhan" sering kali dipaksakan di atas luka yang menganga.
Lalu, mengapa harus mati? Kenapa tidak ada pilihan lain, seperti balas dendam, misalnya?
Balas dendam?! Bisa saja saya lakukan. Namun, saya cukup sadar diri. Menghadapi mereka saja tubuh saya sudah bergetar hebat. Jangankan untuk melayangkan pukulan balik, untuk sekadar mengumpat saja susahnya minta ampun. Lidah saya seolah kelu oleh ketakutan. Daripada harus berakhir dengan mati konyol karena babak belur, saya memilih diam—sebuah diam yang sebenarnya adalah teriakan minta tolong yang tertahan di kerongkongan.
Sebagai korban perundungan, diperlakukan tidak manusiawi seolah menjadi makanan sehari-hari. Namun, sekuat apa pun mental seseorang, jika terus-menerus dijadikan samsak bernyawa, ia akan runtuh juga. Terkadang saya bertanya pada takdir: Kenapa saya harus dilahirkan jika hanya untuk menjadi bahan baku hantam? Pertanyaan filosofis yang menyakitkan inilah yang sering kali memicu niat untuk mengakhiri hidup. Saya pernah berada di titik tergelap itu, mencoba melompat dari lantai dua gedung sekolah, meskipun Tuhan rupanya masih ingin saya tetap menjelajah dunia-Nya. Upaya itu mungkin gagal, namun ada bagian dari diri saya yang mati hari itu.
Andai saja perundungan itu tidak pernah terjadi, mungkin saya masih menjadi Ojam yang periang—anak yang selalu melihat dunia dengan binar mata penuh harapan. Saya tidak akan menjadi Ojam yang sekarang, yang lebih sering mengurung diri di kamar, seolah-olah tidak ada lagi kenikmatan yang bisa ditemukan di luar sana selain dalam kesunyian.
Jika kita melihat maraknya kasus perundungan saat ini, saya rasa media memiliki andil yang besar. Tayangan di televisi kini dipenuhi oleh sinetron bertema cinta monyet yang dibumbui tawuran dan kekerasan. Sangat kontras dengan masa kecil saya dulu, di mana layar kaca masih ramah usia, dengan tayangnya kartun, acara cerdas cermat, hingga legenda "Misteri Gunung Merapi" yang jauh lebih bermartabat.
Dulu, saya sempat bermimpi masuk televisi karena terinspirasi acara cerdas cermat yang dipandu Helmy Yahya. Saya ingin membanggakan orang tua dan sekolah melalui prestasi saya. Namun, seiring waktu, acara-acara bermutu itu lenyap, digantikan oleh tayangan yang secara tidak langsung melegalkan kekerasan. Pupus sudah harapan saya; panggung yang dulu saya mimpikan kini berubah menjadi arena yang menakutkan.
Perundungan juga sebenarnya merupakan cermin dari pendidikan di dalam rumah. Cara orang tua mendidik anaknya adalah fondasi utama. Saya sangat berharap program-program pemerintah seperti "Sahabat Keluarga" dari Kemendikbud bisa benar-benar diimplementasikan dengan baik. Pencegahan perundungan harus dimulai dari meja makan, melalui komunikasi yang hangat antara orang tua dan anak. Sayangnya, pemerintah terkadang abai, banyak program yang dibuat untuk cuanisasi cepat, padahal visi-misinya memberikan banyak manfaat.
Saya membagikan kisah pahit ini bukan untuk mencari belas kasihan, melainkan sebagai sebuah pengingat bagi siapa pun yang membaca ini. Berhati-hatilah dalam bertindak dan berucap. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tapi trauma batin bisa menetap sepanjang waktu. Disakiti itu sama sekali tidak enak. Cukuplah saya dan para korban lainnya yang merasakan pedihnya, jangan biarkan ada korban-korban baru lagi di masa selanjutnya.
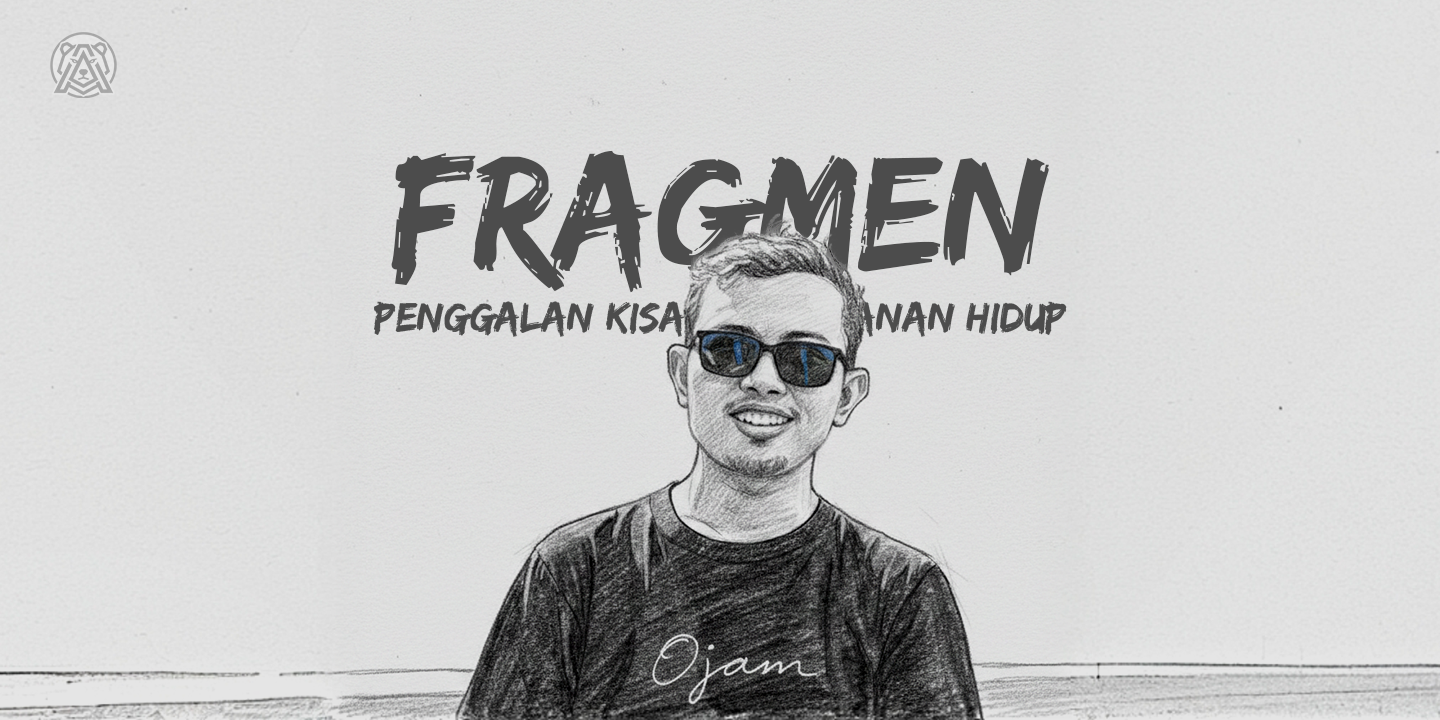
Post a Comment