Di Balik Kesucian Pesantren
Awal mula menapakkan kaki di pesantren, saya merasa seperti kembali dilahirkan. Ada secercah harapan untuk bangkit dari keterpurukan masa lalu sebagai korban perundungan. Teman-teman baru, lingkungan baru—sama sekali tidak terlintas di benak saya bahwa di tempat suci ini, saya akan kembali menjadi mangsa.
Rutinitas saya sehari-hari tak jauh dari pembelajaran. Namun, karena pesantren tempat saya menimba ilmu memiliki aturan ketat soal jam malam—di mana lampu asrama harus dipadamkan—saya sering kali harus mencari celah untuk tetap belajar. Teras masjid atau pos satpam yang lampunya tetap berpijar menjadi tempat pelarian. Bahkan, daripada harus tidur berdesakan di dalam kamar asrama yang penuh sesak setelahnya, saya lebih sering memilih ruang kelas, teras masjid, atau bahkan gudang sebagai tempat merebahkan diri.
Kehidupan di sana mengajarkan kemandirian yang keras. Kami bergantian membersihkan halaman dan asrama sesuai jadwal. Urusan mandi pun menjadi perjuangan tersendiri; keterbatasan fasilitas memaksa kami untuk mandi bersama dalam satu ruangan mini. Bagi yang tidak nyaman dengan kondisi itu, pilihannya hanya satu: melakukannya lebih awal sebelum antrean mulai menyerbu.
Minggu berganti bulan, rutinitas itu menjadi napas baru saya. Hingga pada suatu malam, saya kembali memilih gudang sebagai tempat peristirahatan. Namun kali ini, saya tidak sendirian. Ada seorang teman yang ikut merebahkan diri di sana. Tidak ada pikiran aneh saat itu. Bagi saya, tidur bersama sesama lelaki adalah hal wajar di sini—mandi bersama saja kami biasa, apalagi hanya sekadar tidur bersebelahan dengannya.
Saya meletakkan buku dengan rapi di atas tumpukan buku, menjalankan pesan ustad untuk selalu menghormati media ilmu. Saya menghamparkan kardus sebagai alas dan menggunakan kopiah sebagai bantal darurat. Saat mata mulai terpejam dan kesadaran perlahan hanyut ke alam mimpi, tiba-tiba ada sensasi aneh yang menyelimuti tubuh saya. Sebuah rasa yang belum pernah saya kenali sebelumnya.
Perlahan, saya membuka mata. Jantung saya seolah berhenti berdetak saat menyadari sarung yang saya kenakan telah terlepas. Mata saya terbelalak melihat cairan asing di tubuh saya, dan rasa mual sekaligus ngeri menghujam saat mendapati apa yang sedang dilakukan teman saya terhadap tubuh saya. Ia memperlakukan bagian paling pribadi dari diri saya seolah itu adalah benda tanpa harga diri—menjilatinya layaknya es krim yang akan segera mencair.
Saya ingin marah, saya ingin berteriak, namun tubuh saya kaku tak bergerak. Ada rasa syok yang melumpuhkan saraf-saraf. Kejadian malam itu mengubah segalanya. "Kamu tidak suci lagi, kamu terkutuk," bisikan itu terus terngiang di telinga saya selama bertahun-tahun setelahnya.
Hingga kini, saya masih ketakutan untuk menginjakkan kaki di tempat yang katanya suci. Dan saya pun sering termenung; mengapa di sebuah institusi dengan fondasi agama yang kuat, kejadian kelam seperti itu bisa terjadi? Bertahun lamanya setelah lepas dari sana, saya mencoba mencari jawabannya. Ternyata, kenyataan pahit menunjukkan bahwa kasus serupa memang banyak terjadi, terutama di lingkungan yang sangat tertutup ini. Itulah luka yang saya bawa hingga kini, divalidasi oleh cerita-cerita serupa dari rekan-rekan sesama santri, serta artikel di internet yang berseliweran sana-sini.
Terkadang muncul pengandaian: andai saya tidak masuk pesantren, mungkin saya tidak akan mengalami trauma ini. Namun di sisi lain, jika saya tidak di sana, mungkin saya tidak akan pernah mengerti tentang agama. Sebuah paradoks yang membentuk siapa saya hari ini. Itulah sepenggal kisah saya, sebuah rahasia di balik kitab yang selama ini tersimpan rapat.
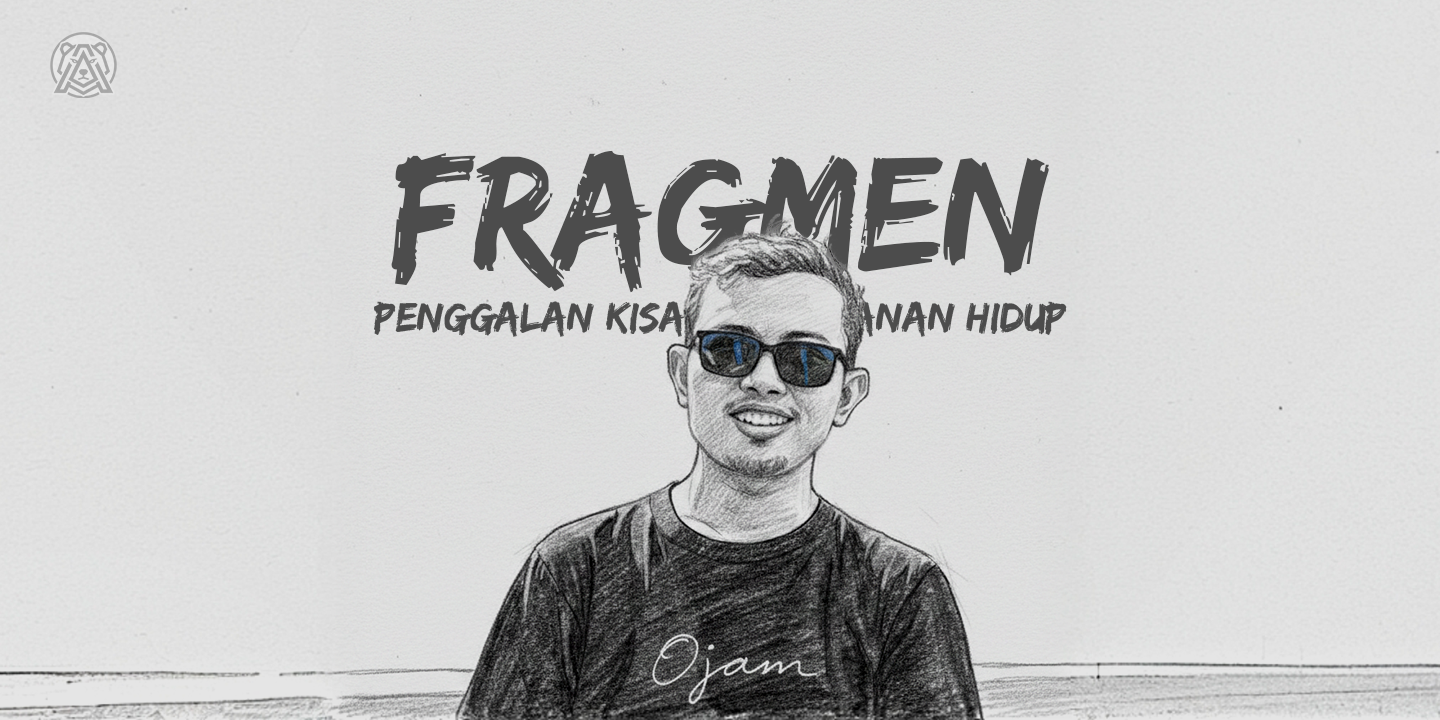
Post a Comment