Merayakan Kebodohan di Negeri Singa
Singapura menjadi titik awal pertama dalam menjelajah panggung dunia. Dengan niat menghadiri konferensi internasional dengan bonus liburan. Perjalanan ini pun menjadi gerbang bagi rentetan pengalaman pertama kali yang menghantam panca indra bertubi-tubi. Semuanya dimulai dari deru mesin pesawat yang membawa tubuh saya melayang di atas awan—sebuah sensasi lepas landas yang selama ini hanya saya saksikan di layar. Di sana, di negeri jiran yang indahnya begitu memanjakan mata, saya merasa seperti bayi yang baru belajar melihat dunia.
Selama di sana, saya tidak hanya berhenti di ruang-ruang konferensi yang kaku. Saya menjelajah setiap sudut kota untuk mencari inspirasi hingga relasi. Saya juga mencoba berbagai wahana ekstrem; membuat jantung saya seperti bom yang berhenti meledak, sementara nyawa saya serasa dicabut malaikat. Di sela-sela teriakan itu, saya menemukan bahagia yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Lidah saya pun diajak berkelana, mencecap ragam kuliner yang namanya pun sulit saya eja, memberikan kejutan rasa yang tak pernah terbayangkan dalam kamus lidah Jawa.
Namun, di balik metafora kota dan wahana, ada tamparan realitas yang cukup keras saat saya menapakkan kaki di ruang konferensi. Di sanalah, ujian mental yang sesungguhnya terjadi.
Berada di tengah kepungan para peneliti dari berbagai negara dengan Inggris sebagai bahasa utama, saya merasa tidak ada apa-apanya. Saya seperti orang paling bodoh di dalam ruangan itu. Setiap kali mereka berdebat dengan diksi yang fasih dan artikulasi yang tajam, saya semakian merasa jauh dari standar. Ada rasa rendah diri yang sempat menyergap; rasa minder yang sangat kuat; serasa modalnya masih sangat pas-pasan untuk jadi hebat.
Meski begitu, sebuah pengamatan yang sedikit memberikan saya napas lega. Melihat para peserta dari Cina—negara adikuasa yang selama ini saya kagumi keberadaannya. Ternyata, kehebatan teknologi mereka tidak selalu berbanding lurus dengan kelancaran berbahasa Inggris mereka. Melihat mereka yang terbata-bata dalam menyampaikan hasil penelitiannya, memicu api tekad di dalam diri saya untuk terus melangkah.
Singapura juga menjadi ajang "cuci mata" yang tak terelakkan. Seperti yang pernah saya tuangkan dalam tarian jemari sebelumnya, mata sipit selalu memiliki magnet tersendiri bagi saya. Di sana, di tengah populasi Tionghoa yang dominan, saya merasa sedang berada di surga visual yang sangat memanjakan.
Di perjalanan ini menyadarkan saya pada satu hal: saya hanyalah seonggok manusia "kecil" dan "bodoh" di dunia ini. Namun, menjadi "kecil" dan "bodoh" di tempat yang tepat adalah sebuah berkah; artinya masih banyak ruang dalam diri yang bisa untuk dijelajah. Dan saya pun pulang dengan tekat kuat untuk kembali menjelajah panggung dunia; ikut berperan dalam kemajuan peradaban.
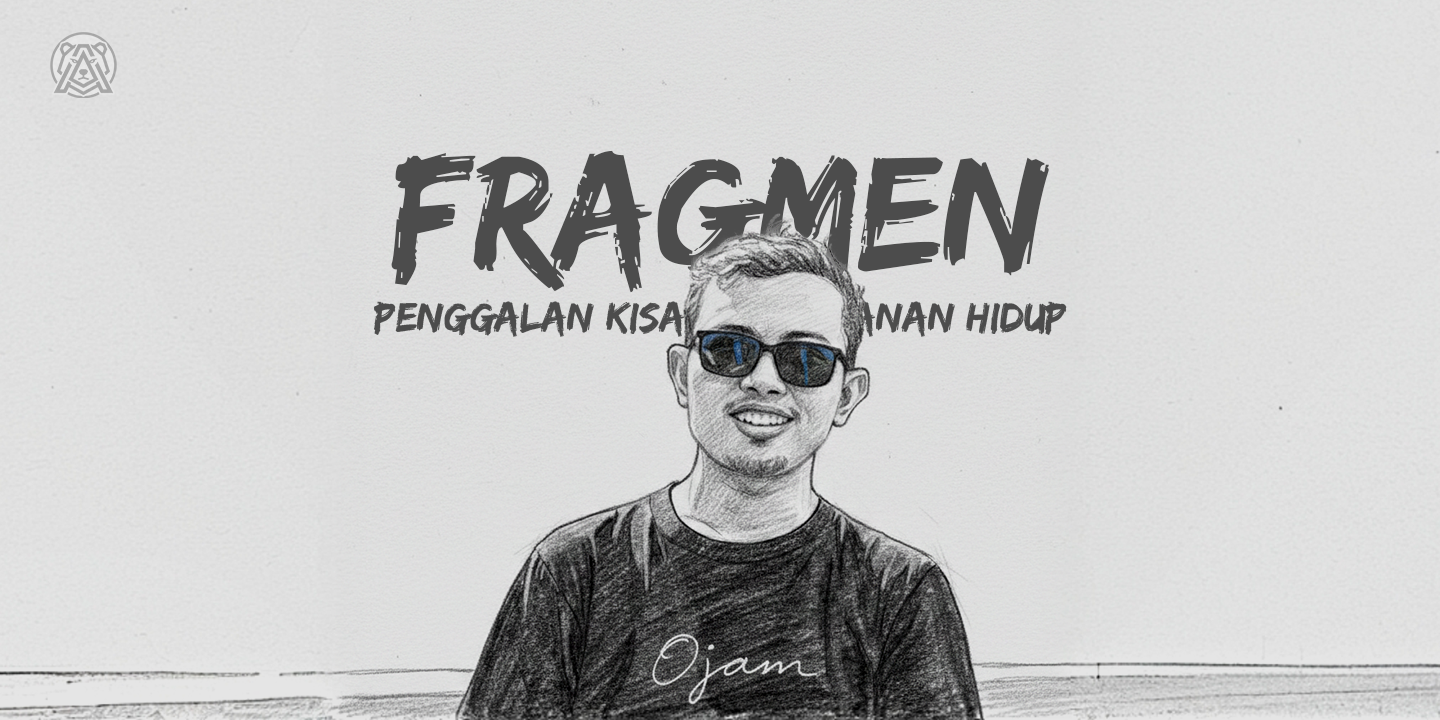
Post a Comment