Bentakan Ego Sang Penguasa Kelas
Dalam dunia akademik yang sedang saya jalani, ada sebuah paradoks yang sering kali membuat saya mengelus dada. Katanya, semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya ia semakin rendah hati—ibarat padi yang kian merunduk saat berisi. Namun kenyataannya, di bawah bayang-bayang gelar mentereng, saya justru menemukan tembok keangkuhan yang sulit ditembus oleh sebuah pertanyaan sederhana.
Kejadian itu bermula di sebuah ruang kelas. Sebagai mahasiswa yang berkecimpung di dunia teknologi dengan perkembangan yang secepat kilat, saya mengajukan sebuah pertanyaan klarifikasi. Pertanyaan yang menurut saya sangat mendasar dan wajar: "Teknologi berkembang begitu pesat, mengapa buku ajar dan materi yang kita gunakan masih menggunakan sumber lama? Apakah ini masih relevan dengan industri saat ini?"
Saya tidak sedang menyerang, apalagi meremehkan. Saya hanya sedang mencari pijakan di tengah arus perkembangan yang begitu deras. Namun, reaksi yang saya terima sungguh di luar nalar. Bukannya jawaban substantif yang saya dapatkan, melainkan sebuah bentakan ego.
Beliau merasa diserang secara personal. "Kamu tidak menghargai usaha saya! Saya ini sudah mati-matian mempelajari buku ini!" serunya. Tak berhenti di situ, gelar S-3 pun dipamerkan sebagai tameng sakti yang menghalalkan segala materi usang. Diskusi yang seharusnya menjadi ajang pertukaran ide, berubah menjadi ajang pembuktian otoritas. Alih-alih menjawab relevansi teknologi, beliau justru sibuk memvalidasi harga diri. Bahkan, selama mengikuti kelas yang diajar oleh beliau, sedikit sekali pembahasan soal materi, isinya hanya membanggakan diri.
Hasilnya? Bisa ditebak. Rasa ingin tahu saya "dihadiahi" dengan nilai yang hancur. Sebuah harga yang mahal untuk sebuah pertanyaan jujur.
Kejadian ini membuat saya merenung. Untuk apa gelar mentereng jika akal sehat tertutup oleh arogansi? Mengapa kerja keras mempelajari sesuatu di masa lalu dijadikan alasan untuk berhenti belajar di masa kini? Dalam teknologi, apa yang kita pelajari "mati-matian" sepuluh tahun lalu bisa jadi sudah menjadi fosil hari ini. Mempertahankan materi lama hanya karena kita merasa lelah mempelajarinya adalah sebuah pengkhianatan terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri.
Mungkin inilah salah satu penyakit di negeri yang sedang "sakit" ini: di mana gelar dianggap sebagai kasta, bukan sebagai tanggung jawab untuk tetap membuka mata. Saya belajar satu hal pahit dari kelas itu: bahwa nilai di kartu hasil studi terkadang bukanlah representasi dari kata cerdas, melainkan representasi dari seberapa patuh kita terhadap ego sang penguasa kelas.
Kelak, jika Tuhan mengizinkan saya berdiri di posisi yang sama, saya berjanji pada diri sendiri untuk tidak menjadi "monster" yang sama. Saya ingin menjadi pendidik yang lebih takut pada ketertinggalan, daripada takut pada pertanyaan mahasiswa yang bernalar. Karena bagi saya, ilmu pengetahuan adalah tarian yang terus bergerak, bukan monumen mati yang terus dipuja dengan hebat.
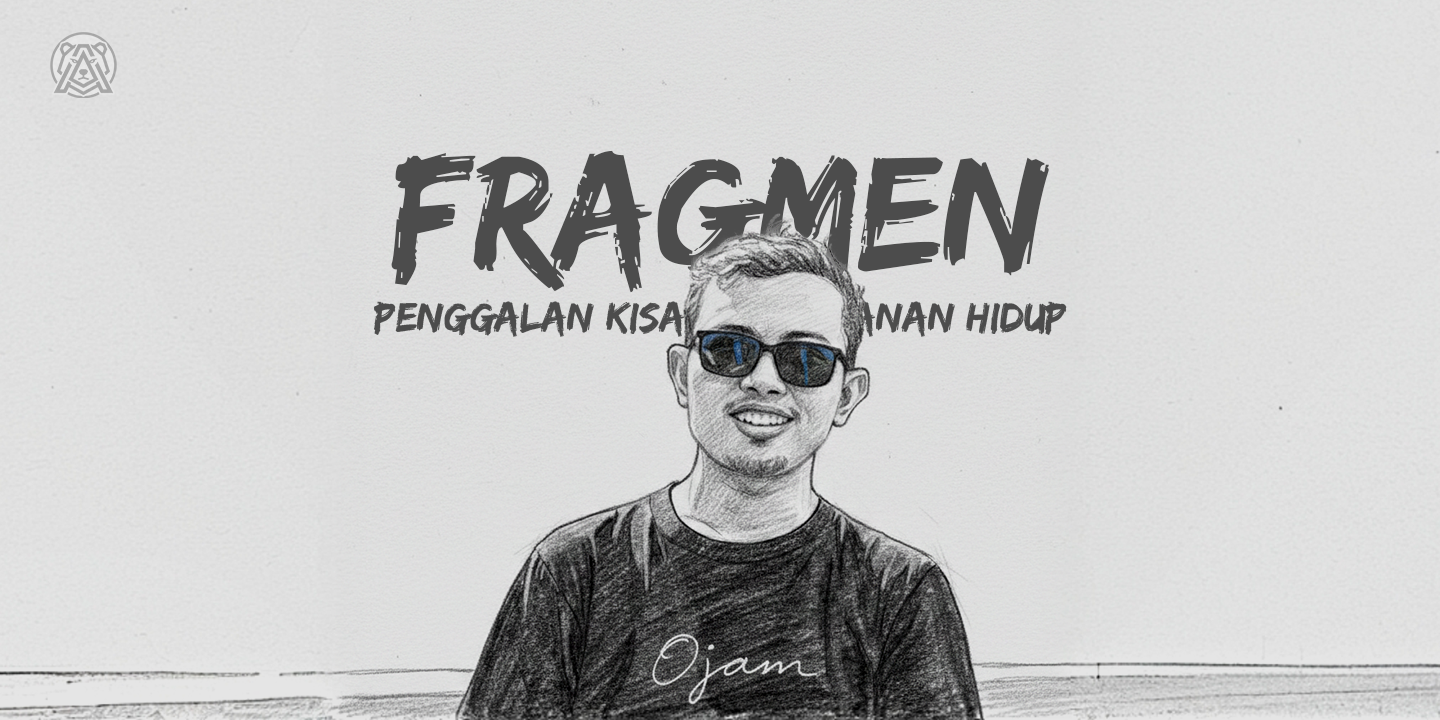
Post a Comment